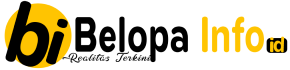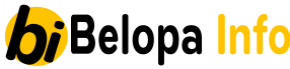Agama punya sejarah panjang. Sebelum era kitab suci atau “Wahyu”, manusia mempercayai mitos-mitos. Pada mitos itu, manusia mengikatkan diri. Melalui mitos, mereka menerjemahkan dan menjalani realitas materi. Aktivitas hidup sesuai terjemahan oleh tokoh karismatik atas mitos-mitos itu.
Setelahnya, datang era logos. Era nalar. Manusia kala itu, kala abad sebelum Masehi masih juga berpegang pada mitos. Manusia tak meninggalkan mitos. Dua perangkat yang digunakan yakni nalar dan mitos. Nalar dan “Ilham”—“agama” tidak terpisah. Dua-duanya dipakai dalam menjalani hidup. Menerjemahkan realitas.
Selanjutnya memasuki era kitab suci atau wahyu. Eropa abad 15 atau abad pertengahan, melalui keuskupan kebenaran terwakili. Tak ada kebenaran di luar gereja. Segala tafsiran tentang semesta harus berlandaskan pada teks-teks suci.
Para pastor memegang kitab suci dengan segala otoritasnya. Agama—kitab suci—menjadi satu-satunya otoritas yang valid dan objektif dalam menerangkan segala dimensi hidup.
Rasio menjadi pelayan yang terbaik bagi kitab suci. Penemuan rasio tak boleh bertentangan dengan kitab suci. Zaman pertengahan ini, kadang kala dinamai dengan abad teologi. Sebuah abad yang menjadikan Tuhan sebagai titik pembicaraan. Segalanya adalah Tuhan.
Dan kitab suci sebagai sabda Tuhan perlu diterima oleh manusia tanpa ada tanya yang panjang. Manusia cukup menjadi pendengar yang baik bagi pastor dalam melantunkan ayat-ayat suci. Sebab pastor adalah manusia “terpilih” untuk menyampaikan sabda Tuhan.
Abad pertengahan mendorong iman objektif yakni keimanan yang dihayati dalam diri yang lepas dari unsur-unsur subjektif—keyakinan sebagaimana adanya Tuhan dan berlaku secara universal.
Abad pertengahan menjadikan petinggi agama sebagai penafsir tunggal dan melahirkan kungkungan terhadap subjek yang ingin bebas berpikir.
Nyatanya, abad pertengahan dengan berpegang teguh pada tradisi keagamaan ternyata tak mampu melahirkan kemajuan. Manusia masih saja terpuruk dalam kubangan derita dan ketakbahagiaan.
Tradisi-tradisi tak mampu menjadi pelipur lara manusia. Namun, sebaliknya tradisi-tradisi keagamaan menjadi beban hidup. Tradisi berubah menjadi mitos-mitos yang melemahkan daya pikir manusia. Melalui para petinggi agama, tradisi selalu diproduksi sebagai keinginan Tuhan yang wajib dilakukan oleh umat manusia, sejatinya untuk menjaga tatanan yang sudah mapan.
Tapi pada perjalanannya, situasi ini ternyata menjadi problem oleh kalangan tertentu. Apatah lagi ternyata situasi ini, dikangkangi oleh para petinggi agama dalam mempertahankan otoritasnya.
Agama pada akhirnya tidak menjadi pelayan kemanusiaan tapi menjadi pengabdi petinggi agama. Kitab suci tidak sedikit ditafsirkan untuk kepentingan kuasa para petinggi agama. Pada kenyataan seperti ini, sebuah keniscayaan bila banyak orang akhirnya menampilkan sikap anti terhadap agama dan ateisme menjadi pilihan yang terbaik.
Dari segi pemikiran, abad pertengahan ditandai dengan semangat totalitas, keutuhan dan kesatuan. Semua tanda-tanda tersebut koheren dan sistematis. Kenyataan oleh pemikir abad pertengahan diandaikan sebagai sesuatu yang hierarkis: Dari yang abstrak hingga yang konkret.
Metafisika tradisional yang fondasi gagasannya pada pikiran-pikiran Aristoteles menjadi filsafat otoritatif. Tafsiran atas pikiran Aristoteles menjadi wacana filsafat dianut dengan baik oleh gereja. Sebab pikiran-pikiran Aristoteles dianggap pikiran yang sangat memadai menjelaskan teologi Kristiani.
Adalah Thomas Aquinas, menjadi puncak pemikiran abad pertengahan. Dialah tokoh yang meneguhkan dengan baik zaman pertengahan ini menjadi abad teologi. Sebuah abad di mana manusia harus menjadi pelayan gereja yang baik. Taat pada setiap norma yang cetuskan oleh gereja.
Tak ada yang boleh berdiri dan mengambil jalan yang lain, sebab itu adalah tindakan bidah dan sesat. Intinya rasio harus tertib pada hukum-hukum gereja. Karena itu, rasio menjadi tumpul melahirkan suatu yang baru. Setidaknya itu yang dirasakan oleh orang-orang belakangan tampil menjadi pemberontak tradisi yang ada. Barangkali memang demikian yang dirasakan oleh sebagian besar penduduk Eropa kala itu. Barangkali karena itu juga, renaisans menjadi tak terindahkah.

Dosen, Penulis, Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Luwu dan Founder Rumah Baca Akkitanawa