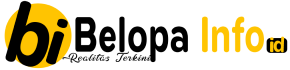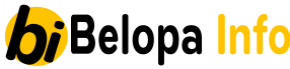Ada berbagai bentuk keacakan, ketidakberaturan, dan ketidakpastian yang memberi warna dalam aneka aspek kehidupan bernegara dan berbangsa akhir-akhir ini, sebagai akibat lemahnya daya “pengendalian” dan hilangnya kekuatan “pengaturan”. Setidaknya, secara implisit itu yang disampaikan oleh Budi Hardiman dan Amir Piliang.
Tubuh bangsa ini seolah dipenuhi berbagai gerak turbulensi sosial (social turbulence), yaitu semacam pergerakan sosial yang tidak beraturan dan acak: wacana politik yang berkembang tanpa arah; wacana ekonomi yang dihantui fluktuasi kronis; wacana sosial yang dilanda kekerasan tanpa akhir; apalagi membincang wacana budaya, yang kini diselimuti oleh ketidakpastian nilai.
Kondisi turbulensi tak terkendali menyebabkan proses demokratisasi berkembang ke arah yang “melampaui” alam demokrasi itu sendiri, yaitu demokrasi tanpa kendali. Kondisi hiper demokratis, ironisnya, telah menciptakan “zona-zona kemacetan” di hampir setiap sistem: kemacetan pada sistem ekonomi; kebuntuan pada sistem politik; kebingungan pada sistem industri; dan trauma dalam sistem sosial.
Secara implisit, Cak Nur pernah berkata bahwa berkembangnya ketidakberaturan, keacakan, dan turbulensi dalam sebuah sistem yang tengah membangun proses demokratisasi merupakan hal biasa.
Bahkan, menurut Cak Nur, dapat bernilai positif, bila ia mampu menggerakkan sistem-sistem demokratis ke arah sifat dinamis bagi pertumbuhan dirinya. Namun, turbulensi merupakan suatu ancaman yang menakutkan bila kekacauan, keacakan, dan ketidakpastian berkembang ke arah lenyapnya kekuatan pengendalian, ke arah kondisi hiper-demokrasi, yang akan menggiring sebuah sistem menuju penghancuran dirinya sendiri atau self destruction.
Kalau kita mengacu pada masa lampau, dalam hal ini apa yang dikenal sebagai Konstitusi Madinah, kita menemukan betapa demokratisnya era tersebut. Di mana orang nomor 1 di dunia menurut Michael Hart, yakni Nabi Muhammad, membangun sebuah sistem yang dapat dikatakan mampu mencover seluruh masyarakat yang hidup di Madinah, apapun agama dan status sosialnya. Bahkan, kata Robert N Bellah, Muhammad mampu membawa masyarakat Arab yang jahil melompat ke arena global berhadap-hadapan dengan imperium yang besar. Sungguh menakjubkan.
Ini menunjukkan, sebagaimana dimaklumi bersama, Nabi memperaktekkan musyawarah, demokrasi, dan peluang terbukanya kritik serta saling adu pendapat untuk kepentingan bersama. Selain menunjukkan arti ini, berdasarkan postulat bahwa sang nabi melakukan sesuatu atas kehendak Tuhan, maka sudah barang tentu Tuhan pun menyarankan hadirnya demokrasi sebagai cara mengamankan hidup manusia.
Izinkan saya mengutip ayat dalam Surah Ali Imran, “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya,” (Qs Ali Imran:159).
Ayat ini menurut tafsir populer adalah bentuk mengafirmasian atas demokrasi. Karena itu, otoritatianisme, dinasti, oligarki, diktatorisme, despotisme, perbudakan, penjajahan, merupakan hal yang bertentangan dengan demokrasi, dan karena itu, juga bertentangan dengan kehendak Tuhan yang menyarankan demokrasi. Sebab, Tuhan yang Maha Kuasa, masih memberi ruang musyawarah. Ini adalah pandangan yang tentu saja amat menarik untuk diperbincangkan.
Namun, dalam sisi lain, agama mengabarkan, atau bahkan menjanjikan sebentuk tatanan ideal di mana suatu masa, entah masa itu kapan, akan ada kepemimpinan absolut di muka bumi ini yang dalam optik Islam disebut sebagai “Mahdiisme”. Lalu kita bertanya, apakah ini merupakan bentuk pembatalan terhadap demokrasi? Di mana sistem Mahdiisme dikabarkan sebagai sistem “maskulin” yang bila diterjemahkan menjadi sangat otoriter?
Terhadap pertanyaan ini, saya akan mengajukan tesis berdasarkan sudut pandang filsafat Islam yang mencintai dimensi transenden dan imanen.
Dimensi transenden yang dimaksud adalah suatu tatanan yang datang dari “atas”. Atau saya sebut saja kepemimpinan ilahiah, yang berbeda dengan apa yang disebut sebagai “Daulah Islamiyah” oleh kebanyakan masyarakat Indonesia.
Itu berarti, demokrasi juga merupakan sistem ilahiah dengan alasan bahwa demokrasi merupakan perintah Tuhan (dari “atas”). Sesuai dengan ini, muncul istilah “imanensi”, yaitu semakna dengan demokrasi. Singkatnya, dimensi imanensi adalah demokrasi.
Melalui sudut pandang ini, kedua dimensi tersebut adalah satu. Namun, demokrasi sebagai aspek imanensi merupakan kondisi ilmiah yang harus dibangun untuk menerima keseluruhan perintah Tuhan yang menjanjikan kepemimpinan mutlak dari dan oleh al-Mahdi atau sebut saja al-Masih, sang penolong.
Saya meminta maaf kepada sidang pembaca lantaran tulisan ini agak panjang, namun izinkan saya memberikan analogi singakat ini; “Menanam biji pepaya jangan harap tumbuh pohon kelapa”. Analogi ini amat jelas, bahwa setiap bentuk akan sesuai dengan potensi yang ada. Begitu juga dengan bentuk sistem mahdiisme, hanya dapat diterima oleh demokrasi sebagai daya di kehidupan kita.
Jadi, tak ada Mahdiisme tanpa demokrasi. Bila tidak demikian, maka Nabi mustahil menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, saat yang sama Tuhan menjanjikan kepemimpinan “absolut”. Itulah kenapa demokrasi merupakan keharusan hidup yang tidak untuk demokrasi, tetapi untuk mempersiapkan hadirnya sistem baru (baca: sistem “absolut”), yang barangkali tak pernah dibayangkan oleh siapa pun di muka bumi ini.
Maka dari itu, melalui tesis ini, tidaklah ditemukan kontradiktori antara demokrasi dan kepemimpinan al-Mahdi. Kita hanya butuh mempersiapkan demokrasi untuk melompat dan menyambut tatanan Mahdiisme. Di mana demokrasi mengandung keterbukaan pemikiran, menjunjung tinggi kemanusiaan, tidak menjual suara dengan harga yang murah, tidak membungkam pendapat, tidak mengambil hak orang lain dan selalu mengajak pada kebaikan.
Apa yang disebut terakhir adalah kondisi ilmiah (imanensi/transendensi) guna menerima aspek rasional Ilahiah (transendensi/imanensi). Dengan kata lain, demokratisasi adalah jalan satu-satunya untuk menerima Mahdiisme sebagai lompatan politik yang spektakuler guna menyalurkan kebahagiaan di muka bumi ini.
Saya tidak yakin apa yang saya utarakan ini dipahami oleh semua orang. Namun saya optimis akan ada diskusi menarik usai tulisan ini dilahap oleh sidang pembaca. Tentu saja kita menghargai kritikan dan keterbukaan pemikiran karena kita mencintai demokrasi. Tetapi bukan untuk mempertahankan yang salah bila kesalahan itu tengah terpampang di hadapan mata. Karena itu, kita tidak hanya terbuka untuk berdiskusi dan saling mengkritisi, tetapi juga kita berharap agar kita semua terbuka terhadap penerimaan atas kebenaran.
Dalam deretan panjang kata-kata ini, karena hari ini hingga beberapa bulan kedepan adalah momen politik, izinkan saya menyampaikan pesan moral kepada saya dan Anda semuanya, “Money politik merupakan perilaku yang menghambat perkembangan demokrasi, dan karena itu money politik adalah praktek pembatalan hadirnya al-Mahdi,”. Terimkasih.
AGUNG ARDAUS: Penulis dan Aktivis JAKFI Nusantara