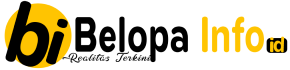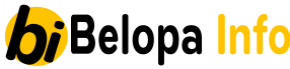Adapun kosmologi Yunani antik menggambarkan alam atau struktur dunia sebagai hierarki berbagai tingkatan eksistensi, di mana yang lebih di bawah di kondisikan oleh waktu, ruang, dan angka, sementara yang lebih di atas ditempatkan di seberang perguliran waktu, kemeruangan dan berbagai keterbatasan lainnya. Pemaparan Platon dan Timaios, bagi Arthur Oncken Lovejoy, menjadi titik awal gagasan Great Chain of Being yaitu:
“…Konsepsi tentang kerangka dan struktur dunia yang, melalui abad 18 kebanyakan oleh mereka yang berpendidikan sekalipun diterima bagi pertanyaan-konsepsi tentang alam semesta sebagai Great Chain of Being terdiri dari sejumlah besar atau tak terbatas, jumlah mata rantai dengan tautan yang membentang dalam tatanan hierarkis mulai dari jenis eksistensi terkecil melewati setiap kemungkinan tingkat hingga sampai ens perfectissimum.
Great Chain of Being merupakan konsepsi yang memandang alam semesta sebagai multidimensi, dan selama berabad-abad merupakan salah satu pandangan paling terkenal dalam filsafat Barat, sains, dan sastra.
Namun seiring berjalannya waktu serta kemerosotan dan dekadensi agama, terutama di Barat, konsepsi semacam ini bertahap dihapuskan sehingga kehilangan signifikansinya, dan beralih menjadi penjelasan alam melalui berbagai peristilahan naturalistik sederhana dan rasional murni, yang mereduksi sumber dan realitasnya sendiri semata-semata pada berbagai sebab dan daya alam; beralih dari penafsiran alam secara simbolik kenaturalisme, dan metafisika kontemplatif ke filsafat rasionalistik.
Great Chain of Being memandang alam dan realitas itu tidaklah satu dimensi. Bahwa alam dan realitas itu bukanlah
“… Subtansi seragam yang datar merentang tak berhingga di depan mata. Tentu saja realitas itu terdiri dari beberapa dimensi yang berbeda tetapi kontinyu. Realitas yang manifes, dengan kata lain, terdiri dari kelas atau tingkat yang berbeda, merentang dari yang terendah dan yang paling padat serta dari yang paling tidak sadar hingga ke yang paling tinggi dan paling halus serta paling sadar. Pada salah satu ujung dari kontinum keberadaan atau spektrum kesadaran ini adalah apa yang kita, di Barat, sebuah materi atau benda mati dan ketidaksadaran, sementara diujung yang lain adalah ‘ruh atau ‘keTuhanan’ atau suprakesadaran (yang juga dikatakan sebagai pokok yang melingkupi seluruh urutan) yang tersusun di antaranya adalah berbagai dimensi lain. Terkadang Great Chain tersebut disajikan hanya memiliki tiga level utama: materi, pikiran, dan ruh. Versi lain memberikan lima level: materi, tubuh, pikiran, jiwa, dan ruh. Yang lain lagi memberikan rincian yang sangat lengkap tentang Great Chain; beberapa sistem yoga memberikan lusinan dimensi diskrit namun kontinyu”
Sebagaimana dinyatakan oleh Charles Taylor bahwa:
“Orang-orang terbiasa melihat diri mereka sebagai bagian dari suatu tatanan yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, ini adalah tatanan kosmis, Great Chain Of Being di mana manusia digambarkan berada di tempat yang tepat bersama dengan malaikat, benda angkasa, dan sesama makhluk duniawi seperti kita”.
Namun, pandangan semacam ini pun kini menjadi terdengar asing dalam pikiran modern. Peradaban Barat modern menolak sama sekali keberadaan struktur hierarkis realitas ini. Maka, struktur hierarkis ini pun digantikan dengan konsepsi realitas datar yang tersusun dari materi belaka serta memang paling cocok diselidiki melalu sains yang mengukuhkan filsafat resmi dalam peradaban Barat modern yaitu materialisme saintifik.
Dalam tradisi ilmiah—struktur hierarkis realitas mulai dari materi, tubuh, pikiran, dan psikis, jiwa, hingga ruh—bisa sepenuhnya direduksi menjadi struktur materi. Sementara materi dalam otak maupun sistem/proses material akan menjelaskan seluruh realitas tanpa sisa. Inilah yang terjadi dalam modernitas yaitu runtuhnya seluruh dimensi interiror atau struktur hierarkis realitas.
Taylor sendiri berkata bahwa:
“…Hanya karena tidak percaya pada doktrin Great Chain Of Being, kita tidak merasa perlu untuk melihat diri kita sendiri sebagaimana diatur dalam alam semesta yang bisa kita anggap sekadar berbagai sumber bahan mentah untuk berbagai proyek kita. Kita mungkin masih perlu melihat diri kita sendiri sebagai bagian dari tatanan yang lebih besar yang bisa menuntut kita. Memang yang terakhir ini mungkin dianggap mendesak. Hal itu akan sangat membantu untuk mencegah bencana ekologi jika kita dapat memulihkan rasa akan tuntutan dari alam sekitar dan padang belantara terhadap kita. Bias subjektivitas bahwa nalar instrumental maupun ideologi pemenuhan yang berpusat pada diri dibuat dominan di masa kita menjadikannya hampir tidak mungkin menyatakan permasalahan tersebut si sini.”
Sebagaimana dinyatakan oleh Lovejoy, bahwa Great Chain of Being ini
“….telah menjadi filsafat resmi yang dominan dari sebagai besar umat manusia beradab nyaris di sepanjang sejarahnya”,
Suatu pandangan dunia yang
“…sejumlah besar pemikir spekulatif yang subtil dan para guru agama besar (baik Timur maupun Barat) telah, dalam beraneka ragam cara, terlibat di dalamnya”.
Bahkan, titik temu yang sama di antara berbagai peradaban yang berbeda ini pulahlah yang mengantarkan Alan Watts untuk menyatakan dengan lebih lugas:
“Nyaris kita tak sadar akan keganjilan yang ekstrim dari posisi kita sendiri dan mendapati betapa sukarnya untuk mengakui fakta gamblang bahwasanya ada satu konsensus filosofis tunggal berjangkauan universal. Hal ini diyakini oleh seluruh kalangan dari berbagai tradisi dan latar belakang yang berbeda yang mewartakan wawasan dan mengajarkan doktrin hakiki yang sama tak jadi soal apakah mereka hidup saat ini atau enam ribu tahun yang lalu, dari New Mexico di Barat jauh atau jepang di Timur jauh”.
Meskipun perspektif semacam ini pernah terjatuh ke dalam masa-masa sulit, namun perspektif ini dihidupkan kembali di era modern oleh Arthur Oncken Lovejoy dalam bukunya The Great Chain of Being (1936) dalam esainya dengan judul yang sama sebagai dikutip di atas.
Signifikansi hal ini di antaranya adalah permasalahan yang seringkali akan membentur siapa pun saat mempelajari filsafat antik, terutama dari masa sebelum era modern, yang terkena bias pandangan dunia yang flat terhadap pandangan dunia yang multidimensi. Jika diumpakan, seperti saat kita melihat dua garis membentuk tanda X dalam bentuk dua dimensi, bisa dipastikan bahwa kedua garis itu memang bersilangan dan bersinggungan. Namun jika tanda X itu berbentuk tiga dimensi kita bis mengatakan bahwa keduanya memang bersilangan, namun apakah pasti bersinggungan.
Huston Smith menuliskan bahwa:
“Alegori gua Platon adalah upaya klasik untuk memberi tahu kita. Bayang-bayang yang dilihat oleh para narapidana yang dirantai itu tentu saja nyata karena bayangan itu eksis dalam beberapa hal dan pada tingkat tertentu, tetapi objek-objek yang membuat berbagai bayangan itu jauh lebih substansial dan dalam pengertian ini mewujudkan lebih banyak eksistensi. Dalam hal memiliki tiga dimensi ketimbang dua, dalam hal melenyapkan bayang-bayangannya serta memanifestasikan independensi lebih pada umumnya maka benda-benda tiga dimensi memiliki sifat kelimpahan lebih besar yang harus dimiliki oleh benda-benda sampai tingkat tertentu jika mereka benar-benar eksis. Ketika salah satu dari tahanan tersebut berhasil melarikan diri dari gua Platon, karakter privatif dari bayangan menjadi jelas, karena bayang-bayang tidak berarti apa-apa kecuali relatif tidak adanya cahaya-cahaya yang kemudian dapat dilihat secara langsung”.

Oleh : Alfathri Adlin
Megister Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta